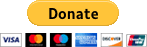Sesekali, tangannya terlihat merapikan posisi tenun ulos berwarna kehitaman, yang menyampir di bahu kanannya.
“Ini ulos langka, bahkan sudah enggak ada yang bikin lagi. Ulos ini namanya gatip-gatip,” ucap dia sambil menunjukkan motif yang tersusun dari deretan benang pada ulos itu.
Wanita itu adalah Devi Pandjaitan, tokoh yang menggagas pelaksanaan pameran ulos bertajuk Ulos, Hangoluan & Tondi mulai 20 September hingga 7 Oktober di tempat itu.
Sore kemarin adalah hari pertama pelaksanaan pemeran.
Devi berdiri di pojok tenda untuk menunggu kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang datang menengok pameran tersebut.
Selama menunggu kedatangan Menkeu, Devi sempat bercerita tentang keberadaan ulos tradisional yang berada di ambang kepunahan.
“Lihat motif ini, ini luar biasa tersusun dari benang-benang alami, luar biasa ini. Tapi sekarang sudah tidak ada yang bisa bikin, sudah punah,” kata Devi sambil mengangkat ujung ulos yang dipakainya.
Devi menyebut, perkembangan masa telah membawa para penenun tradisional batak lebih memilih untuk membuat ulos yang lebih cepat proses produksinya.
Tentu, kondisi ini terjadi karena pertimbangan ekonomi. Keberadaan para tauke pun membuat kehidupan inang-inang penenun ulos tak pernah lepas dari kemiskinan.
“Saya ada 100-an (ulos), tidak semua saya beli, ada sebagian yang saya dapat dari orang. Bahkan ada ibu yang mau meninggal, dan mau memberi ulosnya buat saya,” kata Devi.
“Jadi, ulos-ulos di dalam itu semuanya langka dan usianya sudah mencapai lebih dari 50 tahun, bahkan ada yang 100-an tahun.”
“Sayang kalau itu hanya disimpan saja, maka saya berpikir untuk membuat pameran ini,” sambung dia.
Dalam perhalatan 14 hari ini, ada 50 kain ulos yang dipamerkan. Di antara jumlah itu, ada 25-30 ulos yang merupakan koleksi langka, yang orang Batak sendiri pun belum tentu mampu mengenali motifnya.
Kemiskinan
Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan -yang tak lain adalah suami Devi, menyebut, modal untuk menenun satu ulos sekitar Rp 350.000.
Modal berupa benang itu mereka beli dari tauke yang kemudian menjual ulos tadi ke Jakarta seharga Rp 2,5 juta.
“Berapa yang kembali ke kantong inang-inang? Hanya Rp 250.000 untuk kebutuhan hidup selama membuat satu ulos, yaitu sekitar satu bulan.”
“Tak terbayang bagaimana mereka bertahan hidup,” kata Luhut.
Keterangan serupa diungkapkan Torang Sitorus, tokoh muda yang mendalami tentang ulos.
“Saya sudah melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia, untuk meneliti tentang kain dan tenun.”
“Dari sana saya mengetahui, penenun Batak paling banyak dari segi jumlah, karena kebutuhan kain orang batak banyak sekali,” kata Torang.
Kendati demikian, kata Torang, stok ulos yang ada di pasaran saat ini kebanyakan adalah “ulos mesin” yang tidak berkualitas.
Torang mengaku tak menolak keberadaan “ulos mesin”, namun keberadaan ulos adat pun harus diperhatikan.
“Jangan sampai ini mengganggu ulos adat. Penenun jangan diganggu, karena mereka bikin pakai hati,” kata Torang.
Dia menegaskan, keberadaan ulos mesin dengan kapasitas produksi sehari 30 ulos, tentu tak dapat dibandingkan dengan ulos adat yang memakan waktu tiga minggu untuk sehelai kain.
Mahakarya
Menurut Torang, ulos adalah sebuah mahakarya Toba, yang dibuat dengan teknik tinggi, dan ragam warna yang menggunakan bahan alami.
“Di Toba itu, sebuah ulos dibuat dengan matematik, dihitung benar. Bayangkan saja menganyam benang hingga membentuk motif,” kata dia.
Sayangnya, teknik pewarnaan alam sudah lenyap sejak 50-80 tahun yang lalu.
“Ini saya ketahui dari perbincangan dengan ibu-ibu yang sudah berusia 70-an tahun di sana. Mereka ingat, yang masih menggunakan pewarna alam adalah ibunya,” ungkap Torang.
Usaha untuk membangkitkan pembuatan ulos dengan pewarna alam inilah yang sedang dilakukan.
“Mereka terampil menenun, tapi kurang pengetahuan tentang bahan baku. Itu yang kita lakukan saat ini, untuk mendampingi para penenun agar jangan asal pakai benang,” kata Torang.
Seniman
Hal senada dituturkan Kerri Na Basaria, perwakilan Tobatenun yang juga ikut menggagas pameran ini.
“Melestarikan budaya ulos dimulai dengan menempatkan para penenun bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seniman. Menaikkan derajatnya,” kata Kerri.
“Mereka harus lebih dulu dilepaskan dari belenggu mafia-mafia benang, monopoli. Hingga susah bagi penenun untuk mendapatkan bahan baku.”
Dengan gerakan ini, kata Kerri, diharapkan pada saatnya nanti, para penenun hanya akan berkarya tanpa harus mengerutkan dahi dan berpikir lagi tentang bahan baku.
“Kita lihat, batik, ikat Sumba ‘naik’ jadi kain Nusantara, kita pun ingin ulos pun ‘selevel’ lah,” kata Kerri.
Devi -dalam salah satu bagian kata sambutan di hadapan Menkeu, mengungkapkan niat Yayasan DEL yang menaungi acara tersebut untuk membangun kampung tenun ulos di Sumatera Utara.
Di dalamnya akan ada pendampingan, dan upaya untuk mengangkat kualitas hidup para penenun, serta melepaskan mereka belenggu para tauke yang memerah.
Menurut dia, stigma yang mengidentikan menenun dengan kemiskinan harus lebih dulu dihapus, demi menyelamatkan ulos dari kepunahan. [kompas]