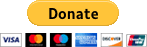Batakpedia.org – Memahami filosofi “Habonaron Do Bona” ternyata telah membawa peradaban orang Simalungun jauh lebih maju dan mampu bertahan dari berbagai tantangan zaman.
Meski agama telah lama masuk ke Sumatra, orang-orang Simalungun tidaklah fanatik dengan agamanya. Mereka lebih menghidupi falsafah mereka yang populer yakni “Habonaron Do Bona”. Jika diterjemahkan, falsafah tersebut berarti kebenaran adalah dasar/pangkal.
Falsafah tersebut begitu kentara dihayati dan diamalkan oleh orang-orang Simalungun, di manapun mereka berada, bahkan ketika mereka berada di tanah perantauan. Jika diperinci, “kebenaran” itu tampak nyata dalam (1) berpandangan benar, (2) berniat benar, (3) berbicara benar, (4) bertindak benar, (5) berpenghidupan benar, dan (6) berusaha benar.
Letkol Purnawirawan MD Purba dalam buku ringkas berjudul Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun (1986) menulis, petuah “Habonaron Do Bona” telah dihayati masyarakat yang mendiami daerah Simalungun sejak lama. Sehingga masa itu, di daerah Simalungun tidak pernah terjadi pencurian, penipuan, dusta, dan perilaku bejat lainnya. Sebab, semua penduduk setempat berusaha hidup benar dan berlaku jujur demi kepentingan bersama. Dusta, mencuri, menipu, dan perbuatan buruk lainnya dianggap sebagai perbuatan rendah dan hina.
“Itu sebabnya, rumah pun tidak perlu pakai kunci. Jika bepergian, cukup menutup pintu dan jendela pakai ganjal supaya tidak terbuka oleh angin atau tidak dimasuki ternak ayam. Orang saling menjaga,” tulisnya (hal.15).
Bahkan, sambung MD Purba, dengan menghidupi pedoman “Habonaron Do Bona “, orang bisa menaikkan status sosialnya. Orang yang terampil menjiwai dan menjalankan falsafah tersebut bisa terpilih atau diangkat menjadi Raja Nagur. (Hal.16). Kerajaan Nagur pertama berdiri di Simalungun pada sekitar abad 8 sampai 15.
Masih menurut MD Purba, sikap hidup orang Simalungun yang amat menjunjung falsafah “Habonaron Do Bona” itu juga tak lepas dari dua hal. Pertama, karena mereka menyadari diri mereka sebagai pendatang yang jauh dari kampung halaman, sehingga mereka menjadi orang yang lebih “tahu diri”, rendah hati dan berusaha untuk saling menolong.
Leluhur orang Simalungun diduga berasal dari Siam atau Champa, Kamboja. Mereka mengembara ke arah Timur dan Selatan dengan mengayuh perahu. Mereka yang menuju selatan berarti bergerak ke arah Kepulauan Nusantara.
Riset terbaru Balai Arkeologi Sumut menunjukkan migrasi manusia pertama kali terjadi di Sumatra kira-kira 12.000 hingga 8.400 tahun lampau. Dan migrasi pertama ditemukan di Nias. Ketua Balai Arkeologi Sumatra Utara Dr Ketut Wiradnyana mengatakan mereka telah mengidentifikasi tulang kaki gajah, batu, dan tengkorak manusia yang ditemukan saat eskavasi. Sedangkan migrasi kedua terjadi di Gayo sekitar 4.000 tahun lalu. Sedangkan migrasi gelombang ketiga diperkirakan terjadi 3.000 tahun lalu. Dan gelombang keempat terjadi sekitar 1.000 tahun lalu hingga 1 Masehi ketika budaya dongsong berkembang pesat di Asia Tenggara. “Paling sedikit telah terjadi lima migrasi di Sumatra,” papar Ketut.
Hasil temuan Balai Arkeologi Sumut juga sepadan dengan riset genetika yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman. Dr Herawati Sudoyo dari Eijkman Institut menyebut, kawasan Indonesia sudah dihuni oleh leluhur yang datang sejak 60 ribu tahun lalu. Tidak hanya memakai metode genetika, Herawati juga menganalisis sebaran bahasa, budaya, dan temuan-temuan arkeologi untuk menguatkan hasil temuannya.
Kedua, karena leluhur Simalungun di awal-awal sempat hidup berpindah-pindah, sehingga ikhtiar ajaran agama tidak begitu mengakar. Meskipun ajaran Hindu dan Buddha sudah lama berkembang. Kendati berpindah-pindah, mereka tetap menjalankan filosofi “Habonaron Do Bona” sebagai suluh dalam kehidupan.
Leluhur Simalungun berpindah-pindah disebabkan serangan penyakit “sappar” atau wabah kolera. Sappar merenggut banyak korban jiwa, sehingga orang Simalungun terpaksa harus mengungsi lantaran, waktu itu, belum ditemukan obat yang bisa menangkal wabah tersebut. Sebagian besar nenek moyang Simalungun mengungsi ke arah Barat dengan menyeberangi Danau Toba menuju ke Pulau Samosir. Sebagian lagi bergerak ke arah Timur ke daerah Selat Malaka yang didominasi penduduk Melayu.
Orang Simalungun yang pergi ke Samosir sebagian menetap di sana dan tak lagi kembali, mereka kemudian mulai terkena “sengat” budaya Batak Toba sehingga mereka mengawini penduduk Samosir. Itulah sebabnya, ada beberapa marga Simalungun di sana, yaitu Purba, Sinaga, Manik (dari Damanik dan Saragi (dari Saragih). Pemakaian huruf “H” perlahan ditinggalkan sehingga jamak kita dengan pemakaian kata “buluh” di Simalungun menjadi “bulu” di Samosir, “ualuh” menjadi “ualu”, “siah” menjadi “sia”, “sappuluh” menjadi “sappulu”, “Saragih” menjadi “Saragi”. Namun karena mereka amat menjaga hubungan kekeluargaan dan pergaulan dengan baik, maka kebudayaan orang Simalungun dengan Orang Samosir tampak banyak kesamaan, termasuk sifat dan bahasa.
Begitu juga dengan pengungsi yang bergerak ke Timur, mereka berusaha hidup dengan baik-benar. Mereka mudah menyatu dengan kaum pesisir dan nelayan dan mengikuti budaya Melayu pesisir. Sebagian dari mereka menetap di Selat Malaka, lainnya kembali ke daerah Simalungun setelah mendapat kabar wabah sappar telah hilang. Sekembalinya ke tanah Simalungun, mereka kembali hidup bertani dan tetap menjunjung kebenaran dan pola hidup marharoan (bergotong-royong).
Memahami filosofi “Habonaron Do Bona” ternyata telah membawa peradaban orang Simalungun jauh lebih maju dan mampu bertahan dari berbagai tantangan zaman. Orang-orang Simalungun juga cukup tahu diri bahwa sebagai perantau, mereka harus survive, sehingga jalan satu-satunya untuk bisa bertahan hidup adalah dengan senantiasa mengutamakan kepentingan umum. Dan sikap itu diwariskan turun-temurun melalui penghayatan terhadap filosofi “Habonaron Do Bona“. (indonesia.go.id)